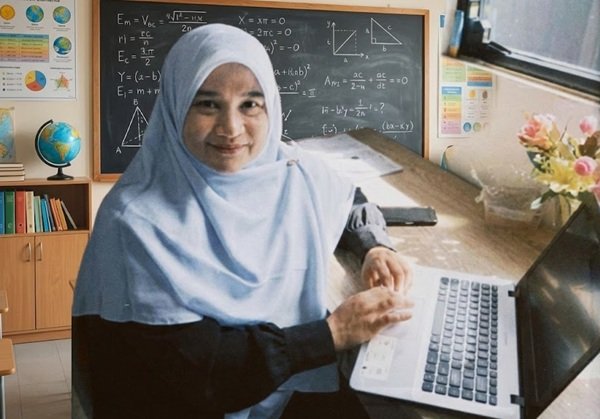“Pendidikan tidak diukur dari seberapa sering kurikulum berganti, tetapi dari sejauh mana perubahan itu benar-benar berdampak pada proses belajar di ruang kelas.”
Oleh: Selvy Yuspitasari
Setiap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kebijakan zonasi sekolah kembali memicu polemik publik. Alih-alih menjadi instrumen yang menenangkan, zonasi justru kerap memproduksi kecemasan sosial, orang tua kebingungan, siswa berprestasi tersisih, dan sekolah kewalahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa zonasi bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan persoalan struktural dalam sistem pendidikan nasional yang belum sepenuhnya siap menghadirkan pemerataan.
Secara normatif, zonasi dirancang untuk menjamin keadilan akses pendidikan. Negara berupaya menghapus dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit dengan mendistribusikan peserta didik berdasarkan kedekatan domisili. Dalam teori kebijakan publik, pendekatan ini sejalan dengan prinsip equity of access. Namun, persoalan muncul ketika kesetaraan akses tidak diiringi kesetaraan kualitas.
Pemerataan yang dibangun di atas fondasi timpang berpotensi melahirkan ketidakadilan baru. Realitas pendidikan Indonesia masih ditandai oleh ketimpangan input pendidikan. Distribusi guru berkualitas belum merata, fasilitas belajar berbeda jauh antarwilayah, dan kapasitas manajemen sekolah sangat beragam. Dalam konteks ini, zonasi cenderung mereduksi persoalan pemerataan menjadi sekadar urusan geografis. Padahal, jarak tempat tinggal tidak otomatis menjamin mutu layanan pendidikan yang setara.
Dampak dari ketidaksiapan sistem ini terlihat jelas di lapangan. Praktik manipulasi data kependudukan, seperti pemindahan kartu keluarga atau penggunaan alamat fiktif, menjadi gejala yang berulang setiap tahun. Fenomena tersebut bukan semata persoalan etika masyarakat, melainkan bentuk resistensi kebijakan (policy resistance) akibat ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan realitas sosial. Ketika sistem tidak memberi ruang keadilan substantif, masyarakat mencari celah untuk bertahan.
Zonasi juga membawa konsekuensi psikologis yang kerap diabaikan. Bagi siswa berprestasi, sistem ini dapat mematahkan motivasi belajar karena capaian akademik tidak memperoleh pengakuan yang proporsional. Sementara itu, sekolah yang menerima lonjakan siswa akibat zonasi belum tentu memiliki kapasitas sumber daya untuk menjamin mutu pembelajaran. Akibatnya, beban pendidikan berpindah lokasi tanpa disertai peningkatan kualitas
Masalah utama zonasi terletak pada pendekatan kebijakan yang parsial. Pemerataan peserta didik dilakukan tanpa diiringi pemerataan sumber daya pendidikan. Dalam perspektif kebijakan pendidikan, zonasi seharusnya diposisikan sebagai bagian dari strategi komprehensif, bukan solusi tunggal. Tanpa investasi serius pada peningkatan kualitas sekolah, kesejahteraan guru, serta sarana dan prasarana, zonasi berisiko menjadi kebijakan simbolik yang gagal menjawab akar persoalan.
Lebih jauh, penerapan zonasi yang seragam di seluruh daerah mengabaikan prinsip kontekstualitas. Kondisi geografis, kepadatan penduduk, dan ketersediaan sekolah sangat bervariasi. Kebijakan yang efektif seharusnya memberi ruang fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan implementasi sesuai kebutuhan lokal, tanpa kehilangan arah tujuan pemerataan.
Oleh karena itu, evaluasi zonasi perlu dilakukan secara menyeluruh dan berani. Pemerintah tidak cukup hanya memperbaiki mekanisme teknis PPDB, tetapi harus menata ulang desain kebijakan secara struktural. Pemerataan guru berkualitas, peningkatan fasilitas sekolah, serta transparansi dan akuntabilitas sistem penerimaan merupakan prasyarat mutlak agar zonasi tidak terus menjadi sumber konflik tahunan.
Pada akhirnya, zonasi sekolah tidak dapat dinilai semata dari niat baiknya, melainkan dari dampaknya terhadap keadilan pendidikan. Jika tujuan utama kebijakan adalah memastikan setiap anak memperoleh pendidikan bermutu, maka pemerataan kualitas harus menjadi titik tolak. Tanpa itu, zonasi akan terus berada dalam paradoks, diklaim sebagai solusi pemerataan, tetapi dirasakan sebagai masalah baru oleh masyarakat.
Kurikulum Terus Berganti, Siapa yang Sebenarnya Siap?
Pergantian kurikulum kembali menjadi perbincangan hangat dalam dunia pendidikan. Dalam beberapa dekade terakhir, pendidikan nasional seolah bergerak dalam siklus yang sama, kurikulum lama dianggap tidak relevan, kurikulum baru diperkenalkan dengan semangat pembaruan, dan sekolah diminta segera menyesuaikan diri. Perubahan ini sering kali dipresentasikan sebagai langkah progresif. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar tetap muncul, apakah seluruh ekosistem pendidikan benar-benar siap?.
Kurikulum memang perlu berkembang. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan tantangan global menuntut pendidikan yang adaptif. Namun, perubahan kebijakan yang terlalu cepat dan berulang justru berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak diiringi kesiapan yang memadai. Inilah persoalan utama pendidikan kita hari ini.
Guru menjadi pihak yang paling terdampak langsung. Mereka dituntut memahami paradigma baru, menyusun ulang perangkat ajar, menyesuaikan metode pembelajaran, sekaligus mengubah sistem penilaian. Semua itu sering harus dilakukan dalam waktu singkat. Pelatihan memang disediakan, tetapi tidak selalu merata dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, banyak guru belajar sambil berjalan, bahkan sambil menebak-nebak arah kebijakan.
Masalah ini diperparah oleh beban administratif yang belum berkurang. Di banyak sekolah, pergantian kurikulum justru menambah jenis laporan, format penilaian, dan tuntutan dokumentasi. Akibatnya, energi guru terkuras pada urusan administratif, bukan pada pendalaman proses belajar-mengajar. Jika kondisi ini terus berlangsung, tujuan kurikulum untuk menghadirkan pembelajaran bermakna akan sulit tercapai.
Peserta didik juga tidak selalu berada dalam posisi yang siap. Perubahan pendekatan belajar dan sistem evaluasi menuntut kemampuan adaptasi yang tidak merata pada setiap siswa. Sekolah dengan fasilitas memadai dan guru yang mendapatkan pendampingan intensif tentu lebih siap dibandingkan sekolah yang kekurangan sumber daya. Tanpa kesiapan sistemik, pergantian kurikulum berisiko memperlebar kesenjangan mutu pendidikan.
Peran orang tua pun kerap luput dari perhatian. Dalam konteks pembelajaran yang semakin menekankan keterlibatan keluarga, orang tua dihadapkan pada istilah, metode, dan pendekatan baru yang tidak selalu mudah dipahami. Sosialisasi kebijakan yang terbatas membuat sebagian orang tua kesulitan mendampingi anak secara optimal, terutama di jenjang pendidikan dasar.
Persoalan mendasar terletak pada cara kita memaknai kurikulum. Kurikulum sering ditempatkan sebagai solusi utama atas berbagai persoalan pendidikan. Padahal, kurikulum sejatinya hanyalah instrumen. Tanpa kesiapan guru, ketersediaan sarana, serta budaya belajar yang mendukung, kurikulum terbaik sekalipun berisiko berhenti menjadi dokumen kebijakan semata.
Perubahan kurikulum seharusnya didahului evaluasi menyeluruh terhadap kondisi riil sekolah. Pelatihan guru perlu bersifat berkelanjutan, bukan sekadar formalitas di awal penerapan. Pendampingan harus konsisten, dan ruang adaptasi perlu diberikan agar sekolah dapat menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokalnya. Stabilitas kebijakan menjadi kunci agar pendidikan memiliki arah yang jelas dan berkesinambungan.
Pertanyaan yang perlu terus diajukan bukan lagi “kurikulum apa yang paling ideal?”, melainkan “apakah sistem pendidikan kita sudah cukup siap untuk berubah?”. Tanpa kesiapan itu, pergantian kurikulum hanya akan memindahkan masalah dari satu kebijakan ke kebijakan berikutnya.
Jika negara sungguh ingin memperbaiki kualitas pendidikan, fokus utama tidak boleh berhenti pada pembaruan kurikulum. Investasi terbesar justru harus diarahkan pada penguatan guru, pemerataan fasilitas pendidikan, dan konsistensi kebijakan. Pendidikan tidak diukur dari seberapa sering kurikulum berganti, tetapi dari sejauh mana perubahan itu benar-benar berdampak pada proses belajar di ruang kelas.
*Penulis Selvy Yuspitasari adalah Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Pamulang (Unpam). Ia aktif menulis dan meneliti isu-isu pendidikan serta kebijakan publik, khususnya terkait pengembangan kurikulum dan profesionalisasi guru.
Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis. Seluruh pandangan, analisis, dan kesimpulan yang disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan sikap, pandangan, maupun kebijakan redaksi, institusi tempat penulis bekerja, atau pihak lain mana pun.