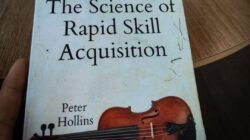“Indeks Kepercayaan Konsumen juga menurun, dan UMKM tulang punggung ekonomi rakyat mulai merasa seperti memanggul beban yang makin berat di punggung yang makin kurus. Petani yang biasanya bisa senyum saat panen, sekarang malah cemberut karena harga jual tidak sebanding dengan jerih payah”
Oleh : Dr.Kemal H Simanjuntak, MBA
Barangkali kita perlu duduk sejenak, menyeruput kopi hitam tanpa gula, dan merenungi kenyataan: Indonesia mengalami deflasi 0,37% pada Mei 2025. Iya, deflasi. Bukan diskon Lebaran, bukan juga promosi Tokopedia. Ini nyata, angka resmi dari Badan Pusat Statistik. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru bersorak.
Turunnya harga barang memang kelihatan seperti hadiah dari langit, tapi kalau isi dompet juga ikutan kempes dan warung tetangga sepi pembeli, kita sedang menghadapi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penurunan harga. Kita mungkin sedang mengalami dompet trauma pasca-Lebaran.
Biasanya, bulan Mei itu semarak. Baru selesai Ramadan, orang-orang masih punya semangat belanja. Pakaian baru, sandal jepit baru, bahkan kulkas pun ikut baru. Tapi tahun ini? Harga cabai merah turun, harga bawang ikut rebahan, daging ayam malah nyaris disangka promo abadi.
Anehnya, bukan karena panen raya atau mukjizat pangan dari surga, tapi karena satu hal: permintaan lesu. Konsumen seperti ogah-ogahan, pedagang seperti kehilangan candaan, dan pasar seolah menatap kosong ke arah keranjang belanja yang tak pernah terisi.
Kita tentu pernah dengar kisah pedagang cabai di Brebes yang katanya lebih sering ngopi daripada ngupas cabai atau tukang sayur keliling yang jualannya balik lagi ke rumah karena langganannya lebih memilih mie instan lima bungkus sepuluh ribu ketimbang sayur bening yang harus dimasak.
Nah, fenomena seperti itulah yang menyusun mozaik deflasi Mei 2025 ini. Tak tanggung-tanggung, dari 90 kota yang disurvei BPS, 65 kota mengalami deflasi. Yang paling parah? Kotabaru, Bima, dan Luwuk bukan nama-nama karakter dalam sinetron, tapi kota-kota yang betul-betul mengalami penurunan harga di atas satu persen. Sebuah rekor yang tidak diidam-idamkan.
Yang bikin hati makin miris adalah inflasi tahunan kita kini hanya 1,60%. Biasanya angka inflasi yang rendah bikin gubernur bank sentral tidur nyenyak, tapi kali ini mungkin beliau justru gelisah. Sebab inflasi rendah itu bukan karena kita sukses menekan harga, tapi karena masyarakat kita sedang menekan hasrat belanja. Seolah-olah dompet dan keinginan sudah sepakat: “Mari kita puasa bersama setelah Lebaran.” Apakah ini berarti kita sedang mengarah ke spiral deflasi? Semoga tidak.
Tapi tanda-tandanya mulai berkedip-kedip seperti lampu jalan yang mau mati. Konsumsi rumah tangga, yang selama ini jadi pahlawan ekonomi Indonesia dengan kontribusi lebih dari setengah PDB tampak mulai batuk-batuk.
Indeks Kepercayaan Konsumen juga menurun, dan UMKM tulang punggung ekonomi rakyat mulai merasa seperti memanggul beban yang makin berat di punggung yang makin kurus. Petani yang biasanya bisa senyum saat panen, sekarang malah cemberut karena harga jual tidak sebanding dengan jerih payah.
Pedagang kaki lima yang biasanya riuh rendah, kini lebih banyak ngelamun sambil menyeka keringat. Dan para ibu rumah tangga, yang biasanya jago mengelola dapur, sekarang harus putar otak lebih keras lagi bukan karena harga mahal, tapi karena isi kantong makin ringkih.
Kita bisa saja menyalahkan geopolitik, El Nino, harga minyak dunia, atau bahkan Mercury retrograde. Tapi sejujurnya, yang kita butuhkan bukan kambing hitam, melainkan sapi yang sehat ekonomi yang kembali bergairah, konsumsi yang kembali berdenyut, dan belanja negara yang tidak hanya cepat tapi juga tepat.
Karena dalam situasi seperti ini, menunggu pertumbuhan ekonomi hanya dari sektor ekspor atau investasi seperti menunggu durian jatuh di tengah kota Jakarta: bisa-bisa nggak pernah kejadian.
Bank Indonesia (BI), tentu, juga sedang berdiskusi keras. Apakah suku bunga yang sekarang ini harus dipangkas supaya likuiditas longgar dan kredit bisa mengalir? Tapi di sisi lain, kalau bunga terlalu rendah, investor asing bisa kabur, rupiah bisa demam, dan inflasi bisa berubah haluan mendadak. Jadi BI pun mungkin sedang merasa seperti sopir ojek yang bingung: gas terlalu kencang takut jatuh, tapi pelan-pelan juga takut ditinggal penumpang.
Pemerintah sebenarnya tidak kehabisan pilihan. Tinggal mau atau tidak. Percepat belanja publik, terutama untuk proyek padat karya yang menyerap tenaga dan memberi nafkah langsung ke rakyat. Jangan hanya bangun jembatan dan jalan tol bangun juga harapan lewat subsidi UMKM yang bukan sekadar bagi-bagi, tapi memperkuat produksi. Kalau bisa, reformasi sistem bantuan sosial: lebih tanggap, lebih pintar, dan lebih akurat.
Di saat seperti ini, jangan harap masyarakat akan percaya dengan pidato penuh jargon. Mereka ingin melihat tindakan. Langsung. Nyata. Dan membumi. Bahkan jika itu hanya berupa penambahan modal usaha Rp1 juta untuk ibu-ibu di pasar, atau pembukaan lapangan kerja dari proyek irigasi desa. Rakyat Indonesia itu tangguh, tapi bukan berarti harus dibiarkan berdiri sendiri di tengah badai ekonomi.
Mari kita belajar dari Jepang, yang pernah terjebak dalam deflasi bertahun-tahun. Mereka punya infrastruktur megah, teknologi mutakhir, dan budaya kerja yang disiplin. Tapi saat konsumsi lesu dan masyarakat menua, mereka pun terseok. Artinya, kita tidak bisa mengandalkan pembangunan fisik semata. Kita perlu membangun manusia dari dapur ibu-ibu sampai mimpi anak-anak muda agar ekonomi kita punya alasan untuk bangkit.
Deflasi ini seolah berkata: “Hei, sesuatu sedang tidak beres!” Tapi alih-alih panik, mari kita jadikan ini alarm. Kadang dalam hidup, seperti juga dalam ekonomi, krisis datang bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyadarkan. Bahwa kita butuh perubahan. Butuh pemikiran yang segar. Butuh langkah yang lebih gesit dari sekadar wacana di konferensi pers.
Indonesia bukan negara yang gampang menyerah. Kita sudah pernah menghadapi badai moneter 1998, pandemi COVID-19, dan naik-turunnya harga minyak dunia. Kita bisa melewati semua itu dan kita juga bisa melewati ini. Asal jangan saling menyalahkan dan saling tunggu. Ekonomi itu bukan urusan elite semata; ia hidup di dapur, di warung, di angkot, dan di dompet kita semua.
Jadi, kalau sekarang kita melihat harga-harga turun tapi senyum masyarakat tak bertambah, itu artinya kita punya pekerjaan rumah besar. Mari kerjakan bersama-sama, dengan semangat gotong royong, dan tentu saja, dengan sedikit humor agar kita tidak terlalu stres. Karena bangsa besar itu bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang tahu caranya bangkit sambil tetap bisa tertawa.
Jakarta, 3 Juni 2025
*Penulis Dr Kemal H Simanjuntak, MBA Konsultan Manajemen | GRC Expert | Asesor LSP Tatakelola, Risiko, Kepatuhan (TRK).