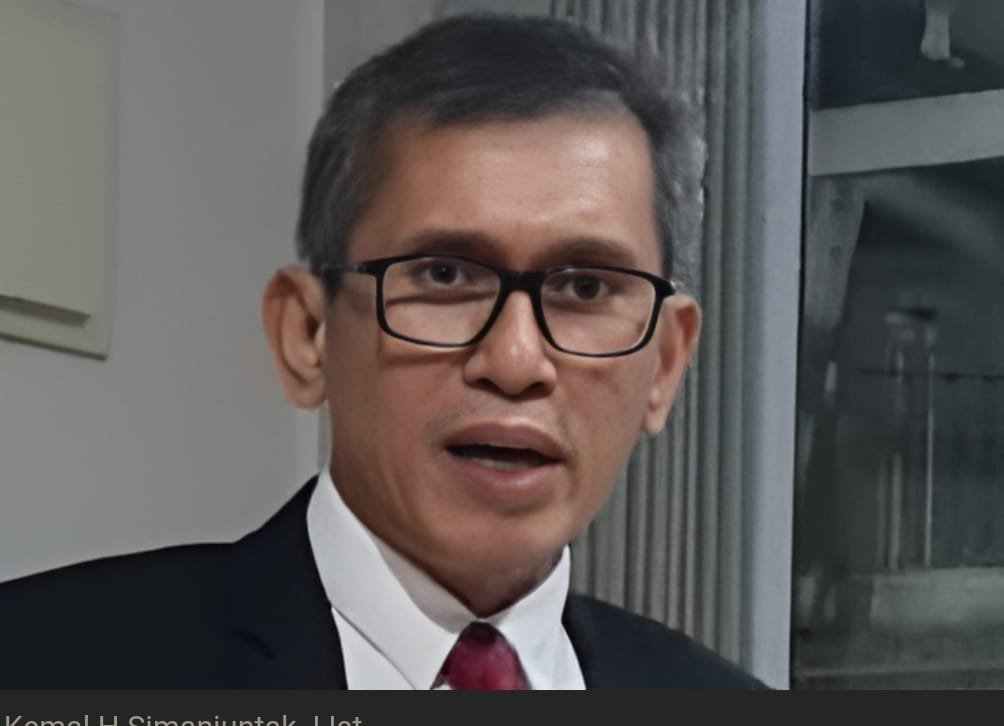Oleh Dr Kemal H Simanjuntak, MBA*
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Dalam konstelasi geopolitik dan perdagangan global yang semakin mengarah pada unilateralisme dan proteksionisme, posisi Indonesia tidak hanya berada di titik rawan, tetapi juga sangat krusial.
Kebijakan tarif tinggi Presiden AS Donald Trump terhadap negara-negara mitra dagang utama, termasuk potensi tekanan ke negara berkembang seperti Indonesia, bukan sekadar perkara pajak impor—tetapi merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memaksa negara lain menyesuaikan diri dengan agenda ekonomi AS.
Strategi ini, yang didorong oleh logika “America First”, cenderung mempersempit ruang gerak negara-negara yang belum memiliki ketahanan struktural dalam sektor industrinya.
Dengan capaian Indonesia yang masih didominasi oleh ekspor bahan mentah dan komoditas rendah nilai tambah, risiko terbesar yang dihadapi adalah ketergantungan struktural yang membuat posisi tawar kita lemah dalam perundingan dagang.
Ketika AS menghapus Indonesia dari daftar negara berkembang di bawah Generalized System of Preferences (GSP), ekspor beberapa produk unggulan terkena imbas tarif lebih tinggi. Peristiwa ini menjadi sinyal bahwa “keringanan” dagang pun bisa dicabut kapan saja jika kepentingan negara besar merasa terganggu. Di sinilah kita menyaksikan betapa rapuhnya ekonomi nasional terhadap perubahan kebijakan eksternal, terutama jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas domestik.
Ketergantungan ini diperparah dengan struktur pasar ekspor yang masih bertumpu pada mitra dagang dominan, yakni China dan AS. Jika salah satu dari dua kekuatan ini—atau keduanya—memutuskan untuk menekan Indonesia, baik secara langsung melalui tarif maupun tidak langsung melalui hambatan non-tarif, maka dampaknya bisa sangat signifikan. Ketergantungan terhadap pasar tunggal bukan hanya membuat Indonesia rentan terhadap guncangan global, tetapi juga mengerdilkan kemampuan kita dalam melakukan diversifikasi produk dan nilai tambah.
Belum lagi, diplomasi dagang kita sering bersifat reaktif dan tidak terintegrasi, di mana masing-masing kementerian bekerja dalam silo tanpa koordinasi yang solid.
Tekanan dari negara besar seperti AS juga tidak lagi bersifat konvensional. Instrumen non-tarif seperti regulasi lingkungan, isu ketenagakerjaan, dan standar keamanan pangan sering digunakan sebagai alat negosiasi terselubung untuk menghambat masuknya produk negara berkembang. Di era pasca-pandemi dan transisi energi global, regulasi semacam ini menjadi senjata strategis yang membungkus proteksionisme dalam narasi keberlanjutan. Jika Indonesia tidak segera memperkuat kapasitas domestik, sistem sertifikasi, dan ketelusuran rantai pasok, maka produk kita akan terus tersandera dalam mekanisme teknis yang sejatinya politis.
Namun, Indonesia tidak sepenuhnya tanpa kekuatan. Ukuran pasar domestik yang besar, struktur demografis yang menguntungkan, serta posisi geografis yang strategis memberi modal penting untuk perundingan dagang yang lebih berani.
Inisiatif hilirisasi nikel dan mineral adalah contoh bagaimana Indonesia mulai berusaha membalik posisi dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi pengendali rantai pasok industri global, khususnya dalam industri kendaraan listrik dan energi terbarukan. Sayangnya, upaya ini belum sepenuhnya didukung oleh sistem hukum yang konsisten dan kepastian investasi yang memadai. Dunia usaha, baik domestik maupun asing, masih mengeluhkan perubahan regulasi yang mendadak dan kerap tumpang tindih.
Dalam konteks tekanan AS, terutama jika Trump kembali memimpin dan membawa serta pendekatan dagang agresifnya, Indonesia berisiko semakin ditekan untuk membuka akses pasar, menurunkan tarif, dan membatasi kebijakan industrialisasi domestik seperti larangan ekspor bahan mentah.
Jika tekanan ini tidak dilawan dengan narasi strategis dan negosiasi cerdas, Indonesia akan kembali ke status quo sebagai negara penyuplai bahan mentah murah. Artinya, semua cita-cita tentang industrialisasi, transformasi ekonomi, dan lompatan teknologi bisa tergadai hanya demi stabilitas jangka pendek.
Lebih jauh, bila kita berhipotesis bahwa Indonesia akhirnya “bertekuk lutut” terhadap tekanan AS, maka hasil akhirnya akan sangat kompleks dan multidimensi. Di sektor industri, keterbukaan pasar tanpa proteksi yang terukur bisa mematikan industri dalam negeri yang baru tumbuh. Di sektor tenaga kerja, tekanan untuk membuka pasar tenaga kerja dan menyederhanakan standar lingkungan bisa mengakibatkan degradasi kualitas kerja dan eksploitasi sumber daya secara tidak berkelanjutan.
Di sisi geopolitik, Indonesia bisa kehilangan posisi tawarnya di ASEAN, karena dianggap terlalu tunduk pada satu kekuatan global, sehingga merusak peran netral dan strategis yang selama ini dibangun dengan hati-hati.
Dalam skenario tersebut, yang paling berisiko adalah hilangnya kedaulatan kebijakan ekonomi. Ketika tekanan dagang berubah menjadi tekanan politik, maka investasi, bantuan pembangunan, bahkan akses teknologi bisa dijadikan alat tukar untuk melemahkan posisi Indonesia dalam isu-isu strategis lainnya, seperti Papua, Laut Natuna, atau proyek-proyek infrastruktur digital. Ini adalah bentuk kolonialisme baru—bukan dengan senjata, tetapi dengan kesepakatan dagang dan tekanan diplomatik.
Untuk menghindari skenario ini, Indonesia perlu membangun ulang arsitektur diplomasi ekonomi yang bersifat lintas sektoral dan berkelanjutan. Diperlukan “task force” yang terdiri atas diplomat, teknokrat, pengacara dagang, dan pelaku industri untuk merumuskan strategi yang bukan hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam membentuk aturan main global.
Kita juga perlu memperkuat posisi dalam forum multilateral seperti G20, WTO, dan ASEAN sebagai jalur tekanan kolektif. Negosiasi dagang bilateral tetap penting, namun harus didasarkan pada prinsip resiprositas, bukan inferioritas.
Ke depan, Indonesia harus berani membentuk narasi sendiri dalam arsitektur ekonomi global—narasi yang tidak hanya bicara tentang komoditas dan insentif fiskal, tetapi juga tentang kepemimpinan dalam transisi energi, ekonomi digital, dan stabilitas kawasan. Dengan begitu, kita tidak hanya bertahan di tengah tekanan, tetapi juga mengambil posisi sebagai pengatur irama dalam pentas global yang terus berubah.
Jika tidak, maka risiko terbesar bukan hanya pada ekonomi, tetapi pada kedaulatan kita sebagai bangsa. (Editor/02)
*Konsultan Manajemen | GRC Expert | Asesor LSP Tatakelola, Risiko, Kepatuhan (TRK)